Ini hanya sepenggal kisah antara aku dan Rafael, adikku. Adik kecil berpipi tembam plus lesung pipit yang membuatnya terlihat semakin manis. Matanya agak sipit (mata milik Papa yang juga diturunkan padaku), hidungnya mancung (itu juga hidung Papa), hanya saja bibirnya tipis seperti Mama.
Tiga tahun lalu Rafael lahir. Di hari yang cerah tepat ketika matahari berada di puncak langit. Adikku juga merupakan kado terbaik yang Tuhan berikan untukku melalui Mama, hari itu tepat hari ulang tahunku yang ke-10. Sebuah kebetulan yang menyenangkan. Walau pada akhirnya perayaan pesta ulang tahunku batal, tapi setidaknya ketika mendengar tangisan petama dari dalam bilik tempat Mama bersalin rasanya begitu senang, gembira begitu melihat bayi yang masih merah yang baru lahir beberapa menit lalu. Dan selama tiga tahun terakhir aku selalu merayakan ulang tahun bersama dengan Rafael.
Awalnya memang senang sekali mendapat adik, apalagi adik yang berbagi tanggal dan bulan lahir yang sama denganku. Juga, sekarang aku sudah punya teman baru untuk kuajak bermain setelah selama sepuluh tahun aku sendirian. Tapi rasa-rasanya semakin lama perhatian Mama dan Papa seluruhnya teredot pada Rafael. Apalagi ketika Rafael sedang dalam masa-masa perkembangan, seperti berjalan dan bicara. Papa dan Mama seolah hanya melihat Rafael, Rafael diutamakan, Rafael dikedepankan.
Aku kesal!
Pernah aku dimarahi karena Rafael menangis–terjatuh karena waktu itu dia sedang belajar berjalan–dan aku tidak menolongnya. Waktu itu aku juga pernah mencubitnya sampai menangis. Ketika Rafael tidak bisa diam dan aku sudah pusing melihatnya. Aku membentaknya. Rafael langsung diam, tapi detik berikutnya ia menemukan mainan baru. sebuah kaleng biskuit dan sendok. Dengan riang ia memukul-mukul kaleng dengan sendok, membuat kamarku bising. Kulit halus yang selama ini kuelus-elus sekarang tanpa berpikir lagi aku cubit keras-keras, dan tentu saja Rafael langsung menangis kencang. Mama datang tergopoh dan langsung memeluk Rafael, menenangkannya. Mama tidak memarahiku, berkebalikan dengan Papa. Aku bisa melihat sorot kekecewaan dari mata Mama, dan itu yang membuatku benar-benar menyesal. Aku sudah mengecewakan Mama. Alhasil aku mengurung diri di kamar seharian, menolak makan minum.
Sampai malam harinya aku tidak bisa tidur, aku lapar. Seharian aku tidak makan. Perlahan aku menuruni tempat tidur, mengendap-endap menuju dapur.
Dapur tampak begitu gelap dan senyap. Dengan memberanikan diri–walaupun dalam hati aku takut sekali–aku membuka pintu kulkas dan menemukan beberapa buah sosis sisa kemarin siang.
Ketika aku mendengar suara langkah kaki aku segera bersembunyi di bawah meja makan, berharap yang datang bukanlah hantu atau maling. Tiba-tiba lampu dapur menyala dan aku bisa melihat kaki kurus Mama dari bawah sini. Terdengar suara cician air, juga dentingan gelas dengan meja di atasku. Dalam hati aku bersyukur itu hanya Mama. Tapi aku juga tidak bisa keluar begitu saja dari tempat persembunyian ini.
Aku kembali memakan sosis yang ternyata masih kupegang sambil memerhatikan lantai kramik, dan tahu-tahu Mama sudah berjongkok di depanku, melihatku dengan bingung. Aku yang kaget langsung berdiri, lupa jika diatasku ada meja dari kayu. Kepalaku terbentur cukup keras, sosis yang kupegang langsung jatuh. Ugh… sakir sekali! Jika saja aku tidak sedang mendiamkan Mama mungkin aku sudah menangis dan berhambur ke arahnya.
Masih kuingat pertanyaan Mama yang bernada khawatir, “Chika ngapain di sini? Chika gak apa-apa?” yang kubalas dengan satu gelengan sekaligus untuk dua pertanyaa tadi. Aku tidak mau menjawab pertanyaan Mama, dan tentu saja kepalaku sakit.
Mama menarikku–yang hampir-hampir menangis–dari tempat persembunyianku. Mama membawaku ke kamar, lalu ikut tidur bersamaku. Saat itulah aku mulai memberanikan diri bertanya.
“Ma, apa Mama sudah gak sayang lagi sama aku?”
Mama hanya tersenyum sambil mengelus-elus kepalaku lembut. Rasanya sudah lama sekali tidak tidur dengan Mama, karena terlalu sering bersama Rafael.
“Tentu saja Mama sayang sama Chika.” Kini Mama beralih mengelus pipiku, lalu menyingkirkan beberapa helai anak rambut dari sana.
“Terus kenapa Mama sama Papa sama adik terus?”
Lagi-lagi Mama tersenyum, “Rafael itu masih kecil, Chika. Masih butuh penjagaan Mama dan Papa, masih butuh perhatian lebih.” Aku bisa mendengar deru napas Mama yang panjang-panjang, “Waktu Chika kecil juga begitu, malah dulu Chika lebih dimanja. Mungkin karena dulu cuma Chika anak Mama. Tapi sekarang ada Rafael, dan Chika sekarang sudah besar.
“Rafael masih dalam tahap perkembangan. Mama dan Papa harus bantu dia supaya bisa tumbuh dengan baik. Mama harus bantu dia belajar berjalan, belajar bicara. Makannya Chika gak boleh marah karena perhatian Mama dan Papa terpusat ke Rafael, semuanya wajar.”
Aku balas memandang Mama. Apa semua yang dikatakan Mama barusan benar? Apa perhatian lebih Mama dan Papa untuk Rafael hanya karena dia masih kecil, masih butuh bimbingan, perhatian lebih? Kalau begitu aku bisa benapas lega.
Malam itu juga Mama tidur denganku, masih mengusap kepalaku sambil menyanyikan lagu pengantar tidur. Kupeluk Mama erat-erat. Aku tidak mau jauh dari Mama, aku tidak mau semua perhatian Mama padaku berkurang, juga Papa. Tapi aku mengerti sekarang. Rafael, adikku masih kecil. Tidak sepantasnya aku marah padanya, dia masih belum mengerti apa-apa. Bukan maunya diperhatikan, tapi dia memang butuh. Aku sebagai kakak harusnya bisa mengerti dan mengalah.
***
Kini adik kecilku sudah besar, sudah bisa berlari dan berbicara (meskipun sering tersendat). Dan yang lebih penting, perhatian Mama dan Papa kini sudah terbagi rata. Tidak ada yang dilebihkan, tidak ada yang dikedepankan, didahulukan. Kasih sayang mereka kini sama rata.














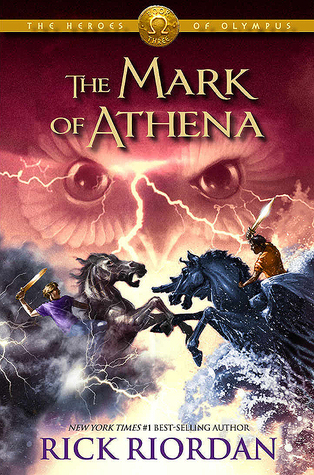




0 komentar:
Posting Komentar